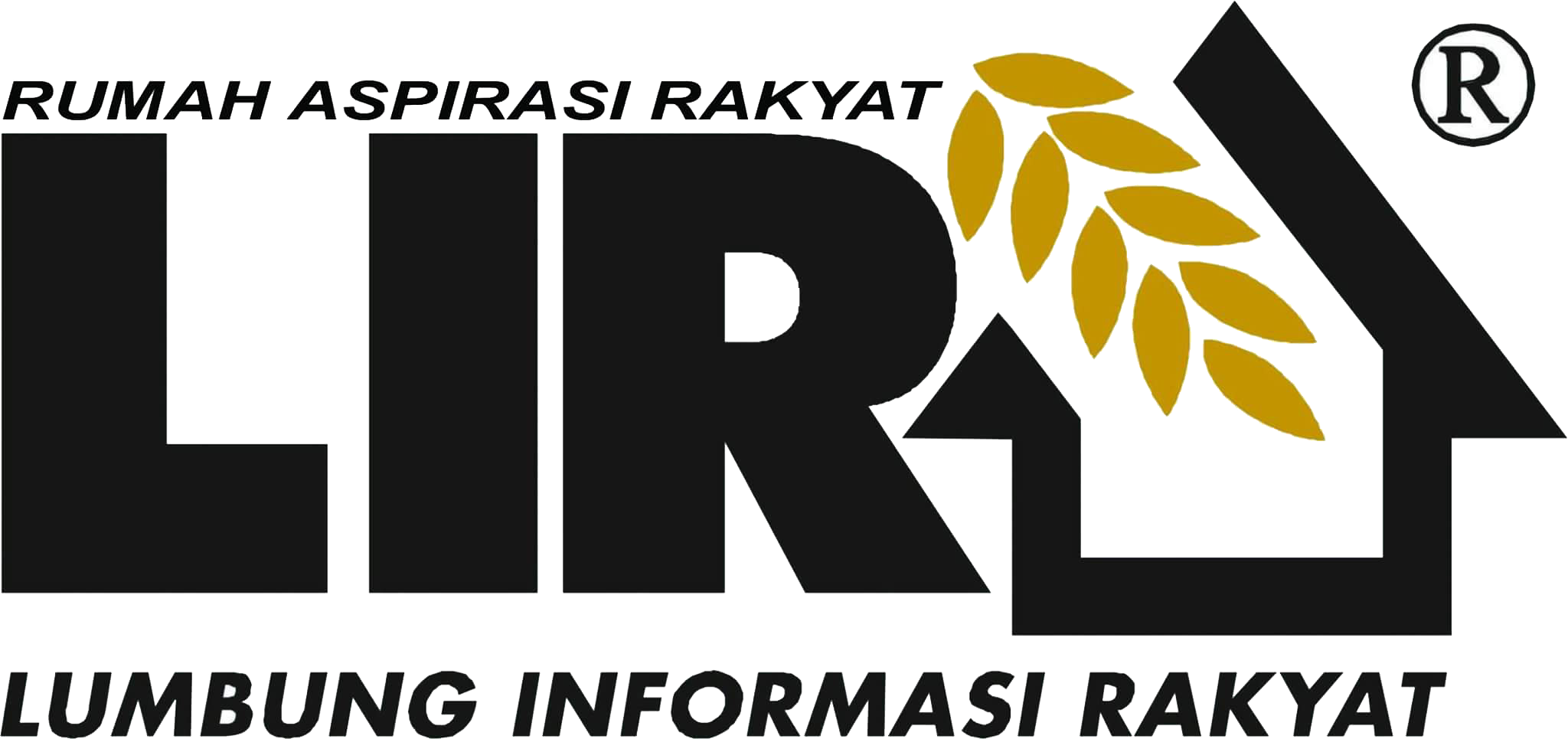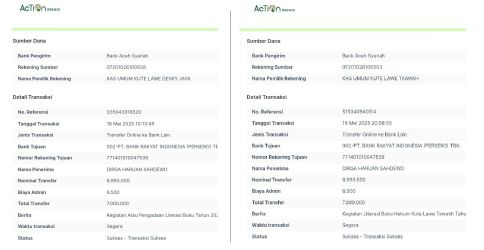Menyoal Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Undang-Undang

PRO-KONTRA terkait putusan MK Nomor 135/2024 yang pada pokoknya memerintahkan pembuat UU memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah bergulir tajam saat ini.
Kelompok yang mendukung putusan MK berpegang pada argumen kefinalan putusan MK dan, sembari secara satir, mempertanyakan sikap yang berseberangan telah menerima putusan MK lainnya tanpa reserved, khususnya putusan MK Nomor 90/2023 yang melancarkan keterpilihan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Di arus berlawanan, argumen yang diteriakkan bertumpu pada tuduhan inkonstitusionalitas putusan MK karena bertabrakan dengan norma UUD 1945, khususnya pada norma keajegan waktu Pemilu per 5 tahun sekali. Putusan MK dianggap melangkahi norma ini.
Perdebatan ini penting dan menarik, tidak hanya terkait relasi dan kewenangan lembaga negara, tapi juga menyangkut kesepakatan tentang model pemilu masa depan yang selalu berubah.
Secara akademik, isu ini akan memantik diskusi serius yang akan membongkar lebih dalam teori dan konsep fundamental keilmuan tatanegara dan politik.
Namun, ada satu aspek yang perlu dibahas lebih awal, dan ini belum muncul dalam obrolan tema ini, yakni menyangkut praktik yang sudah berjalan, tentang peran MK sebagai penafsir UU, bukan UUD semata.
Bentuk Tafsir UU
Penafsiran UU selama ini merupakan kewenangan pembentuk UU yang wujudnya berupa penjelasan UU. Secara doktrinal maupun positivistik, penjelasan UU dianggap satu kesatuan dengan UU dan karenanya dapat dijadikan objek pengujian di MK.
Dalam wujud selanjutnya yang lebih kongkrit, UU diinterpretasikan juga oleh lembaga-lembaga yang diberikan kekuasaan distributif melalui pembentukan peraturan seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan KPU, Peraturan Presiden, bahkan sampai Peraturan MK.
Dua model interpretasi teknis UU ini telah jadi pegangan semua ahli hukum negeri ini. Sampai kemudian MK, sebenarnya sejak lebih dari satu dekade lalu, memainkan peran baru menerima permohonan pengujian UU dengan model konstitusional atau inkonstitusional bersyarat yang konstruksi amar putusannya memberikan tafsir terhadap kata, frasa, atau pasal dalam UU yang dianggap sesuai konstitusi.
Ketika pertama kali muncul model amar putusan MK yang bersifat interpretatif ini, perdebatan timbul dengan mengedepankan teori-teori seperti positive vs negative legislator atau judicial activism vs judicial restraints. Hebatnya, tanpa halangan politik yang signifikan, kecuali pemberhentian salah satu hakim MK oleh DPR dengan alasan sering berseberangan dengan pemberi mandat, praktik amar putusan ini telah menjadi preseden atau yurisprudensi, bahkan belakangan masuk dalam ketentuan melalui PMK Nomor 2 Tahun 2021 terkait hukum acara pengujian undang-undang di MK.
Melalui praktik ini, maka secara teknis perundang-undangan, ada model baru tafsir UU, yakni tafsir versi MK. Hebatnya, tafsir ini lebih tinggi posisinya ketimbang tafsir yang dibentuk oleh lembaga-lembaga negara dalam bentuk peraturan karena putusan MK setara dengan UU.
Peran MK menjadi penafsir UU merupakan ekstensifikasi kewenangan. Tak pernah ada penolakan terhadap posisi MK sebagai penjaga dan penafsir konstitusi. Bahkan pemahaman umum yang muncul di kalangan komunitas hukum, MK seakan dijadikan penafsir tunggal konstitusi. Namun, terkait fungsi MK menjadi penafsir UU melalui putusan pengujian UU, sebenarnya belum final legitimasinya.
Persoalan Yurisprudensi
Sebagai pewaris sistem kontinental, Indonesia pada dasarnya tidak menjadikan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum. Tapi sejak MK hadir, pelan-pelan pendulum sistemik ini berubah. MK secara konsisten menerapkan asas stare decisis dalam putusannya. Mahkamah Agung pun mulai secara rutin menetapkan putusan-putusan tertentu sebagai yurisprudensi dengan penulisan khusus dalam buku pedoman khusus terbitannya. Meski tidak dituliskan, yurisprudensi tampaknya telah jadi sumber hukum tak tertulis negara ini.
Penerimaan preseden ini memang telah jadi model global di mana sekat sistemik, misalnya, antara common law dengan civil law tak lagi ketat. Setiap sistem saling berkelindan dan melengkapi, meski tidak secara tegas dinyatakan dalam aturan hukum setiap negara. Bentuk sistem hukum sebuah negara hanya terlihat dari infrastruktur hukum fundamentalnya. Isi dalamnya saling bertaut dengan konsep dari sistem lainnya karena memang, meminjam konsep perbandingan hukum, proses transplantasi hukum telah menjadi sesuatu yang lumrah.
Tapi, dalam konteks negara kita, apakah model yurisprudensi MK ini telah benar-benar terintegrasi secara sistemik, atau dengan kata lain apakah ini telah mendapat legitimasinya secara hukum dan politik?
Secara konseptual, yurisprudensi belum jadi sumber dalam sistem hukum kita. Asas legalitas ala kontinental mengunci hukum hanya bersumber dari pemegang otoritas yang dikasih legitimasinya oleh rakyat, baik langsung atau tidak, dan dalam bentuk peraturan. Norma dalam bentuk putusan baru dikenal belakangan, terutama secara progresif dan intensif dilakukan oleh MK.
Di negara berbasis kontinental, yurisprudensi dapat ditransformasi menjadi kebiasaan. Kebiasaan atau lebih dikenal dengan adat (custom) telah diterima secara global sebagai sumber hukum. Dalam hukum Islam, ini bahkan jadi kaidah pokok yang melahirkan banyak kaidah turunan, yakni al 'adat muhakkamah (adat dijadikan hukum). Pertanyaan yang muncul di sini adalah, apakah praktik yurisprudensi ala MK telah memenuhi unsur sebagai kebiasaan? Di sini letak perdebatan bisa muncul.
Dalam sistem hukum Islam sendiri, sesuatu bisa dikatakan ‘adat atau ‘urf harus memenuhi syarat tertentu. Salah satunya adalah sudah ajeg dalam rentang masa tertentu digunakan sebagai hukum dan diterima oleh komunitasnya.
Terkait dengan syarat penerimaan adat atau kebiasaan ini secara legalistik tidak ada aturan baku yang spesifik. Kalau pun ada, yang dimaksud di sana lebih pada komunitas adat yang harus dilindungi dengan mandat konstitusi pula. Bukan dalam aspek kebiasaan sebagai sebuah sumber hukum. Tak ada kata sepakat secara doktriner terkait ini.
Dalam kasus putusan MK yang berisi amar berupa tafsir UU, meski model ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan diterima dalam praktik, apakah ini telah diakui legitimasinya secara hukum dan politik, masih sesuatu yang belum dipastikan. Namun penerimaan putusan MK sepanjang sejarah berdirinya, meski ada juga yang tidak dilaksanakan oleh pembentuk UU seperti pada kasus Perppu Ciptaker yang kemudian diafirmasi sendiri oleh MK, bisa jadi indikator awal untuk menilai ini. Terlihat keajegan di sana, meski ada juga ruang negasi atau setidaknya keraguan.
Jika model putusan MK yang berbentuk interpretasi UU belum sepenuhnya legitimate dari sisi kebiasaan yang sudah jadi sumber internasional, pengaturannya dalam bentuk Peraturan MK, tentu punya masalah tersendiri. Beberapa akademisi telah mengeritik posisi hukum acara MK dalam wujud PMK. Sebagian berpendapat harusnya aturan MK dikodifikasi dalam bentuk UU, bukan peraturan. Alasannya agar memberikan kepastian hukum dan tidak berubah cepat.
Masuknya model amar putusan terkait (in)konstitusional bersyarat dalam PMK, memang tidak memiliki dasar langsung dari UUD maupun UU. Model ini adalah murni hasil ijtihad MK dalam upaya mewujudkan otoritasnya sebagai penafsir konstitusi yang sudah dimulai sejak tahun 2008 melalui putusan Nomor 10/2008 untuk putusan konstitusional bersyarat dan putusan Nomor 4/2009 untuk model inkonstitusional bersyarat.
Pemikiran MK berpijak pada asumsi tak mungkin menafsirkan konstitusi dalam proses pengujian UU hanya dengan menyatakan norma UU itu inkonstitusional tanpa menegaskan apa bentuk norma UU yang konstitusional melalui pemaknaan baru.
Di sini, MK mempraktikkan kaidah fikih "ma laa yatimmu al waajibu illa bihi fa huwa waajib" (apa yang dengannya sebuah kewajiban tak dapat dilaksanakan, maka hukumnya adalah wajib). Tindakan menafsirkan UU menjadi wasilah untuk penegakan konstitusi. Ini berbasis pada adagium fikih lainnya yakni "al wasaa’il fi hukmil maqhoshid" (Perantara hukum sama hukumnya dengan tujuannya).
Menafsir UU di sini dipandang sebagai tindakan instrumental oleh MK dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai the guardian of the constitution. Yang jadi soal dalam sistem hukum kita yang positivistik adalah apakah model instrumentatif itu sesuatu yang sah dan dapat diterima secara hukum? Tentu jawabannya dikembalikan pada sikap terhadap kedudukan yurisprudensi dalam sistem hukum kita.
Open Legal Policy
Aspek lain yang jadi persoalan terkait amar putusan MK yang berisi pemaknaan hukum baru, bahkan terhadap norma teknis, adalah ketidakjelasan wilayah kebijakan hukum terbuka (Open Legal Policy/OLP).
Istilah yang khas MK ini, karena tidak ditemukan di referensi hukum lain, sengaja diciptakan MK untuk memberikan demarkasi kewenangan konstitusional MK dengan pembentuk UU. Sayangnya, frasa ini tak ada makna definitifnya. Tak ada satu pun makna denotatif dari istilah asing ini dalam putusan MK. MK sengaja mengambangkan maknanya untuk, suatu saat, kemungkinan disimpangi sendiri.
Dalam kasus pengaturan waktu dan teknis pemilu, misalnya dalam putusan terkait usia capres dan cawapres, MK mengabulkannya setelah menolaknya beberapa kali karena dianggap OLP. Apakah pemisahan pemilu nasional dan daerah juga merupakan OLP? Ini masuk ranah abu-abu. Justru karena itu, jadi ruang yang bisa diintervensi MK. Keabu-abuan OLP menjadi persoalan hukum tersendiri karena memunculkan ketidakkonsistenan MK dalam menghadapi pengujian norma.
Dalam putusan 135/2024, terbaca dengan jelas bahwa pijakan pertimbangan MK bukanlah didasari pada aspek abstraksi norma semata, tapi secara nyata berdasarkan pada fakta-fakta kongkrit pelaksanaan pemilu sejak 2004 hingga 2024. Ada kesan kuat, MK bertindak sebagai evaluator pelaksanaan pemilu. Evaluasi ini secara padat mencakup pelaksanaan pemilu, pilkada, penyelenggara pemilu, hingga peran parpol. Puncaknya adalah fakta bahwa pembentuk UU tidak mengubah UU Pemilu sebagaimana diamanatkan MK melalui putusan-putusannya.
Aspek faktual, dalam berbagai putusan MK, sering diabaikan dan dianggap bukan bagian dari kewenangan MK karena dipandang sebagai aspek teknis yang masuk dalam ranah pelaksanaan norma atau jadi wilayah OLP. Namun anehnya, dalam putusan ini, justru evaluasi faktual ini yang jadi pintu masuk MK untuk menggunakan kewenangannya menilai konstitusionalitas norma yang diuji dan kemudian melahirkan amar putusan dengan redaksi yang sangat panjang sebagai sebuah tafsir atau makna baru dari norma asal pasal-pasal yang diuji.
Terhadap OLP ini hendaknya ke depan MK memberikan batasan dan indikator yang jelas yang dapat dipegang bersama sehingga memberikan kepastian hukum. Jangan sampai MK sendiri menciptakan “makhluk hukum” baru yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum.
Kekuasaan Legislasi
Terlepas apapun persoalan teknis hukum yang muncul menanggapi putusan MK ini, hal lain yang jadi perhatian di sini adalah sifat final putusan MK yang ditegaskan konstitusi. Putusan MK tidak final hanya dalam urusan terkait pendapat DPR mengenai pemakzulan presiden dan/atau wakilnya karena harus mendapatkan persetujuan mayoritas mutlak MPR.
Namun apakah ini berarti pembentuk UU tidak boleh menyimpangi putusan MK? Jika dikembalikan pada prinsip pembagian kekuasaan, hakikatnya pemegang kekuasaan legislasi ada di pembentuk UU, yakni DPR/DPD dan Pemerintah. Dalam beberapa kejadian, pembentuk UU sering mengabaikan putusan MK. Misalnya dalam norma pemidanaan publikasi hasil survei di masa tenang. Setiap perubahan UU Pemilu, pembentuk UU tetap memasukkan norma pidana ini meskipun sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Sampai akhirnya MK sendiri yang menyatakan mengubah pendiriannya mengikuti kehendak pembentuk UU untuk menyatakan norma pemidanaan ini menjadi konstitusional.
Jika UU Pemilu diubah secara total, maka sejatinya pasal yang ditafsirkan MK dalam putusannya dengan sendirinya kehilangan eksistensinya. Pertimbangan MK dalam putusannya dengan situasi ini hanya akan menjadi pedoman semata. Sifat kefinalan putusan MK tetap terjaga, tapi karena objek pasal yang dimaknai baru telah tiada dengan lahirnya UU baru, maka putusan itu pun kehilangan kekuatannya.
Yang utama adalah rasio dan logika konstitusi yang diterapkan MK dalam putusan dipertimbangkan seraya melaksanakan rekayasa konstitusional untuk membentuk sistem pemilu yang ideal. Proses legislasi yang dilakukan haruslah melibatkan partisipasi luas dalam rangka menemukan format baru pemilu yang sesuai asas dan prinsip konstitusi. Pembentuk UU yang melahirkan UU dengan prinsip keterbukaan, dilakukan dengan hati-hati dan mendalam, tanpa tergesa-gesa akan menegaskan kekuasaan legislasi yang diharapkan.
Sejatinya, putusan MK yang isinya banyak memberikan tafsir baru UU adalah kritik kuat kepada pemegang kekuasaan legislasi agar menggunakan kekuasaannya dengan baik dan maksimal untuk kepentingan rakyat berbasis pada konstitusi. Dengan mandat yang diberikan rakyat melalui pemilu, semestinya pembentuk UU dapat menggunakan kekuasaannya untuk memproduksi hukum yang berbasis pada kehendak rakyat yang diwakilinya. Jika UU yang dihasilkan berkualitas optimal secara prosedural dan substansial, maka MK ke depan tak perlu repot lagi bertindak selaku penafsir UU.(*)